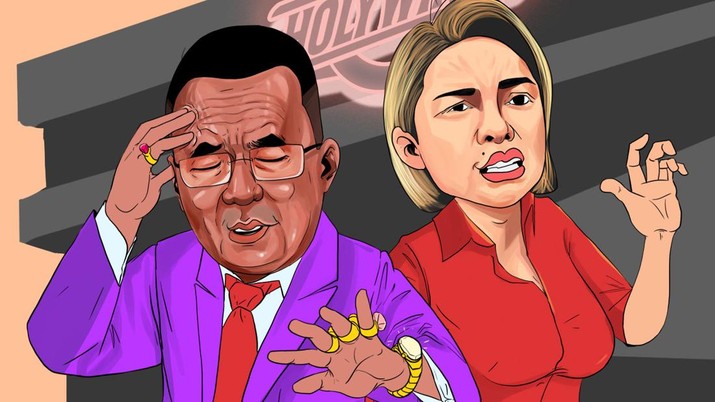Pelita.online –
Direktur Eksekutif Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Raynaldo Sembiring menilai Undang-Undang Cipta Kerja menyuburkan potensi konflik lahan seperti yang dialami masyarakat adat Besipae, di Desa Pubabu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Raynaldo menyebut UU Ciptaker bakal mereduksi keterlibatan masyarakat karena pemerintah ingin mempercepat dan memudahkan perizinan berusaha.
“Ketika ada reduksi partisipasi masyarakat dalam Amdal dan kecepatan perizinan, maka ada potensi besar masyarakat tidak well informed terhadap proyek yang akan masuk. Maka involvement terbatas. Dan hal yang gitu akan membuat konflik. Ketika usaha jalan, masyarakat tidak dapat info yang layak,” kata Raynaldo kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Senin (19/10).
Raynaldo mengatakan terjadi perubahan ketentuan mengurus Amdal dalam Pasal 26 UU Ciptaker dari yang tertuang di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pasal 26 UU Ciptaker mengatur bahwa analisis dampak lingkungan (Amdal) disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan atau kegiatan.
Sementara di UU 32/2009, penyusunan Amdal harus melibatkan masyarakat yang terdampak, pemerhati lingkungan hidup dan yang terpengaruh atas keputusan dalam proses Amdal.
Raynaldo menilai penyusunan Amdal harus melibatkan seluruh masyarakat, bukan hanya yang terkena dampak langsung dari kegiatan usaha tersebut. Menurutnya, kegiatan usah pasti berkembang lebih besar dan membuat dampak semakin luas ke masyarakat.
“Bisa jadi sekarang yang terkena dampak sekitarnya saja. Tapi ketika usaha terus berkembang dan sudah menghasilkan produksi, limbah, tenaga kerja, mungkin akan lebih banyak lagi (masyarakat yang terdampak),” katanya.
Lebih lanjut, Raynaldo mengatakan penyusunan Amdal kini hanya dianggap sebagai proses administrasi belaka. Padahal, tujuan menyusun Amdal untuk memetakan dampak dan meminimalisir konflik dari kegiatan berusaha tersebut. Untuk memetakan hal tersebut, partisipasi masyarakat tidak bisa dibatasi.
Ia menjelaskan konflik lahan umumnya terjadi karena Amdal dan izin berusaha tidak disusun dengan baik dan suara masyarakat diabaikan.
“Amdal di-speed up sebagi dokumen bersifat administrasi saja. Lalu terbitkan izin. Masalahnya ketika izin diterbitkan, perusahaan atau pemerintah merasa daerah tersebut sudah layak diusahakan. Tapi masyarakat berpikir bahwa mereka juga punya hak,” ujarnya.
Selain perkara Amdal, Raynaldo berpendapat masalah tata ruang untuk proyek strategis nasional dalam UU Ciptaker juga bisa melahirkan konflik lahan. Hal ini dikhawatirkan bakal mengabaikan keberadaan masyarakat adat jika pemetaan wilayah tak dilakukan dengan baik.
Kebanyakan konflik lahan dipicu oleh penolakan masyarakat terhadap proyek di wilayahnya. Salah satunya seperti konflik yang berujung bentrokan sampai pembakaran rumah di Desa Pubabu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT.
Konflik antara masyarakat adat Besipae dan Pemprov NTT sudah dimulai sejak 1982. Mulanya karena proyek percontohan intensifikasi Peternakan Besipae (penggemukan sapi) yang dicanangkan gubernur NTT saat itu.
Untuk menjalankan proyek tersebut, pemerintah meminta masyarakat desa Oe Kam, Mio, Polo dan Lunanmnutu menyediakan lahan. Mereka menyetujui dengan syarat rumah, kebun, dan taman milik masyarakat di area proyek tetap dikelola masyarakat.
Namun belakangan masyarakat adat tak mau melanjutkan kontrak proyek tersebut. Konflik pun terus menggulung sejak 2017 sampai saat ini. Teranyar konflik mengakibatkan pembakaran rumah milik warga adat Besipai oleh sekelompok orang tak dikenal.
Sumber : cnnindonesia.com